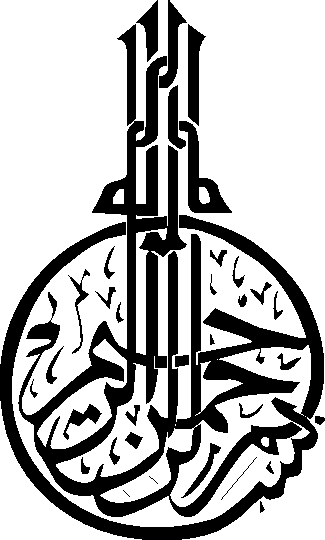
ENTAHLAH
AKU JUGA NGGAK TAHU
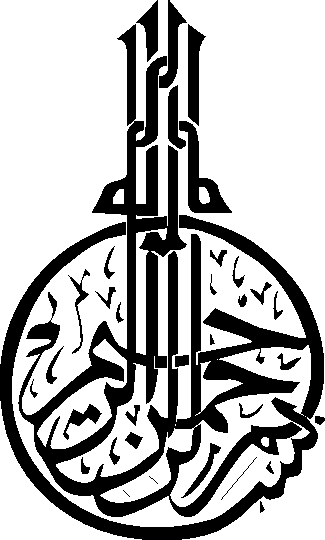
|
MENILIK GLORIFIKASI SEJARAH DALAM EPISTEMOLOGI ISLAM Mempersepsi Islam, sesungguhnya tidak berbeda dengan menghadirkan kembali gambaran mitologis masa kenabian dan tarik ulur kuasa politik abad tengah. Dimana kebenaran dogmatika dikonstruksi, dirajut kerangkanya, dibangun temboknya untuk kemudian dikukuhkan hasilnya. Bila demikian, maka dimensi apapun dalam wacana Islam pada dasarnya adalah sisa-sisa masa lalu. Pengukuhan jejak sejarah itu ternyata hingga saat ini diwarisi oleh pola pendidikan Islam. Karenanya kritik wacana agama menjadi niscaya ditengah konstruksi epistemologi yang terpenjara oleh masa lalu. Pendidikan Islam tak punya kejelasan para-digmatik. Demikian kira-nya yang terjadi dengan pendi-dikan Islam saat ini. Lon-taran kritis yang sedemiki-an keras itu tak lagi asing ditengah sema-ngat zaman yang makin me-ngarah pada nuansa prag-matis. Geliat kritis atas perkembangan pendidikan Islam ini merupakan akibat responsif terhadap kelesuan epistemologis yang diidapnya. Rapuh tidaknya rancang bangun epistemologi pendidikan Islam pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa jauh ia dapat menjadi ruang representatif bagi suburnya diskursus transformatif realitas kontemporer yang merangsang peserta pendidikan untuk mencipta, bukan mengulang. Hingga fase ini perguruan tinggi islam, baik IAIN ataupun STAIN sebagai representasi utamanya, ternyata masih berkutat pada kerangka lama yang sudah tidak lagi konteks dengan ruang-waktu kontemporer. Hal ini praktis menyisakan konstruksi pikir mahasiswa yang selalu berputar-putar pada perdebatan-perdebatan lama pula. Sementara Zeitgeist global yang tak pernah berjalan mundur memaksa para akademisi untuk selalu responsif terhadap transformasi masal disemua lini kehidupan. Sebagai ilustrasi sederhana, wacana teologi (kalam) sebagai salah satu kajian utama dalam perguruan tinggi Islam dapat dijadikan permisalan. Tenggang waktu yang demikian jauh, antara abad tengah dengan abad modern seakan tak mempengaruhi kajian-kajian diskursif perdebatan tentang kalam sendiri. Soal-soal klasik yang semestinya diperbaharui dan dikritisi, seakan tak bergeming. Tradisi pemikiran tentang ‘tradisi’ justru semakin menemukan taringnya untuk mendaulat diri sebagai ‘gharu qaabil linniqash wa attaghyiir’. Lantaran perdebatan kritis dalam perguliran wacana keagamaan tidak pernah tumbuh secara wajar, maka pada ujungnya terjadilah stagnasi. Padahal Islam yang saat ini ada merupakan lapisan-lapisan arsip hasil sejarah beserta tarik-ulur kuasa konflik politis pada masa lampau. Pemikiran Islam kemudian hanya dianggap sebagai doktrin suci yang taken for granted. Ia tidak boleh dikupas dan harus diakui kebenarannya begitu saja tanpa diperlukan kajian dan telaah serius terhadap latar belakang yang mendorong pemikiran keagamaan tersebut. Walhasil, hal ini selalu menimbulkan sikap apatis terhadap kritik dan sifat emosional yang makin lama makin kuat. Untuk lebih jauh menilik kubang stagnasi dan kerapuhan rancang bangun epistemologis pendidikan Islam, sejarah dari perspektif kritis sosiologis dengan mengetengahkan teks yang sengaja dilianglahatkan oleh narasi besar sejarah Islam, patut dimunculkan kembali. Sehingga sejarah, yang merupakan salah satu episteme yang menjadi sebab utama pengaruh stagnasi epistemologis pendidikan Islam, dapat dikritisi dan digelar kembali dengan perspektif baru. Mengupas sejarah tak harus berpatok pada paradigma lama, dengan merunutnya secara linier, kronologis dan tanpa kritik. Sebaliknya sejarah harus didekati layaknya jejak-langkah para pengembara yang berserakan disana-sini tanpa harus mengubur teks-teks yang kontroversial dengan kuasa dominan. Inilah yang bagi Foucault dinamakan dengan telaah arkeologis. Biarkan siapapun berbicara atas perspektifnya masing-masing. Sejarah Islam; antara Lokalitas dan universalitas Bila menengok kembali khazanah histories pemikiran Islam sejak awal munculnya Islam dengan pengalaman kenabian sebagai tolok ukur keberagamaan, niscaya akan terlihat bahwa sebenarnya dasar acuan doktrin Islam sangat terikat pada lokalitas wilayah Arab, baik yang mencakup aspek-aspek material maupun institusi bangsa Arab ketika itu. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, antar lain; Pertama, doktrin tentang keyakinan bahwa ada kekuatan absolut yang maha Satu yaitu Allah. Khalil Abdul Karim, melalui verifikasi sejarah Islam dalam bukunya ‘Quraisy min al-Qabiilah Ilaa al-Daulah al-Markaziyyah" menunjukkan bahwa didalam menda’wahkan ketauhidan, Muhammad sebagai pembicara otoritatif Islam ternyata tidak melakukan babat alas. Sebelum Muhammad menjadi nabi dan menerima wahyu, para penyair asketik ‘Hanifiyyah’ Arab telah banyak yang membuat puisi-puisi ‘Tauhid’. Dalam puisi-puisi itu, mereka mendoktrinkan adanya keyakinan tentang adanya Allah yang Satu, Penyayang, Pengampun, Pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Bahkan tentang janji kubur, siksa kubur, janji surga dan ancaman neraka. Hal ini berarti bahwa, disatu sisi, kaum hanifiyah sebetulnya telah menjalankan peran peran ‘kerasulan’ dengan merubah kerangka ideologis yang marak di Arab ketika itu, politeisme, kepada kemurnian tauhid. Di sisi lain, mereka berperan ‘mengarahkan perhatian’ bangsa Arab kepada agama langit yang bukan Yahudi mapun Nasrani (waktu itu Yahudi dan Nashrani adalah agama impor yang masuk ke bangsa Arab). Narasi sejarah versi Khalil ini mengatakan bahwa waktu itu (sebelum Muhammad menjadi rasul, Red) telah tercipta opini publik yang dilegitimasi oleh orang-orang Ahli kitab dengan keyakinan mitologis bahwa sudah saatnya Allah menurunkan rasulnya kepada bangsa Arab. Karena itu tidak sedikit dari kaum hanifiyyah yang berusaha meraih wahyu kenabian tersebut. Untuk itu mereka dengan sangat ketat menjalankan ‘tradisi ibrahim’ yang hanif, beribadah disekitar ka’bah, thawaf, beri’tikaf dan bertahannust digua-gua. Bahkan Muhammad muda diceritakan juga pernah menjadi murid kaum hanifiyyah ini. Oleh karena itu ketika Muhammad mendapat wahyu di gua Hira’, beberapa dari kaum hanifiyyah tidak percaya. Salah satu yang kuat menolak hal itu adalah seorang hanifiyyah yang alim dan beriman kepada Allah —seperti dikatakan diatas bahwa kepercayaan tentang Allah Yang Esa telah ada- bernama Umayyah bin Shalt. Diceritakan oleh Khalil, bahwa Umayyah merasa sudah mendapat enam dari tujuh tanda kedatangan wahyu. Kurang satu tanda saja ia akan menjadi rasulallah. Sehingga menurutnya, tidak mungkin Muhammad mendapatkan wahyu sebagai utusan Tuhan, sebab spiritualitas yang dijalani masih dibawahnya. Ia bahkan merasa bahwa ini adalah rekayasa Muhammad saja. Didalam sejarah Islam kemudian, posisi Umayyah menjadi unik, karena ia yang seorang alim dan beriman, justeru tidak mengikuti agama yang dibawa Muhammad. Sebaliknya, Abu Thalib yang tak beriman justeru menjadi pendukung utama Muhammad. Jadi, seruan Tauhid Muhammad adalah bagian dari lokalitas kepercayaan terhadap Allah yang mulanya telah bergaung di sekitar Makkah, khususnya kaum hanifiyyah. Kedua, dalam konteks sosio-politik, Khalil menunjukkan ‘bukti’ kuat bahwa Muhammad SAW adalah seorang Arab yang aktif mengolah mitos "Ratu Adil ala Timur Tengah kuno’. Mitos disini adalah sebuah narasi besar dari tindakan bersejarah bangsa Arab untuk mencapai sebentuk kedaulatan politik. Dan mitos itu berbentuk dua anugerah sekaligus, antara Nubuwah wa al-mulk (kenabian dan kekuasaan). Sesungguhnya cita-cita untuk menguasai bangsa Arab telah dipancangkan oleh kakek buyut Muhammad bernama Qushai bin Kilab setelah memegang kunci ka’bah. Selanjutnya perumusan tata pemerintahan dan ekonomi dilakukan oleh putera dan cucunya. Bahkan format ‘teokrasi’ yang berpola al-Diin Yuroodhu al Daulah (agama melahirkan negara) pada dasarnya telah disiapkan oleh kakek Muhammad, Abdul Muthalib. Ia terinspirasi oleh bangunan epistemology ideologis kerajaan Romawi dalam suatu kunjungan dagangnya. Disini Muhammad diposisikan sebagai sosok yang mempunyai dua gelar itu sekaligus. Dalam kaitan dengan mitos Arab tersebut, Muhammad Ahmad Khalafallah, dalam disertasinya yang bisa jadi sangat kontroversial, ‘al-Fann al-Qashashi fi al-Qur’an al-Kariim (Genre sastra kisah didalam Al Quran al Karim), memperkuat bukti bahwa keberadaan Muhammad dalam tarik ulur kuasa politis Arab ketika itu sangat erat. Dengan melegitimasi mitos-mitos kisah dalam alqur’an dia mendaulat diri sebagai utusan Tuhan. Sebab Khalafallah sendiri menunjukkan bahwa mayoritas kisah-kisah dalam al Quran bukanlah sebuah deskripsi sejarah yang riil, cerita tentang nabi-nabi misalnya. Sebaliknya kisah kisah tersebut merupakan mitos yang diciptakan untuk mendorong, menemani, menghibur, mengingatkan, membuka harapan dan mengarahkan bangsa Arab untuk bergerak bersama dalam melahirkan tatanan sosial yang lebih baik. Belum lagi bila memperhatikan paradoksi tarik-ulur psikologis dalam diri Muhammad, antara kepribadian yang ‘super human’ (menyukai laku prihatin, sangat peka, toleran, welas asih, penyabar, tidak suka bertikai) dengan keputusan perang sebagai implikasi dari aspirasi keagamaan dan politik yang dibawanya. Begitulah kompleksitas dan ketidaksederhanaan posisi kenabian Muhammad di dalam lokalitas sejarah bangsa Arab. Namun diatas segalanya, Muhammad SAW dengan seperangkat nilai-lokalitas itu dapat mengantarkan bangsa Arab menuju kemenangan gemilang dan mengkonstruksi tata nilai masyarakat Arab dan dunia Islam menjadi sangat kuat. Dia kemudian menjadi sosok pemimpin sekaligus rasul yang mempersatukan sekaligus menjaga kekuatan infrastruktuktur bangsa Arab. Setidaknya sejarah kenabian, dari teks-teks kontroversial tersebut diatas yang —meminjam pola arkeologi Michel Foucault— dikubur oleh kuasa dominan berupa episteme yang beroperasi diselingkup konstruksi keberagamaan umat Islam saat ini, menjadi pemahaman bahwa doktrin agama, sesuci apapun klaim doktrin itu, tak harus dipertahankan dan dikukuhkan tanpa boleh disentuh, dikaji dan dikritisi, sebab ia tak dapat lepas dari konstruksi lokalitas perkembangan dogmatikalnya. Sebaliknya ia memerlukan kajian ulang serius untuk memberikan kontekstualisasi doktrin, apakah ia dapat beriringan dengan zaman ataukah justeru stagnan. Nah inilah yang saat ini hilang dari daya pikir umat Islam. Tentunya sepenggal narasi kecil diatas, yang berada diluar nalar para pelajar Islam saat ini, menjadi sangat menggelisahan. Sebab dipihak lain mereka telah begitu dalam menancapkan keteguhan iman bahwa Islam beserta seperangkat doktrin dogmatikalnya adalah ajaran yang ‘Shoolihun Likulli Zaman Wa Makan’ (Universal disetiap waktu dan tempat). Islam bagi mayoritas muslim adalah nilai yang orisinal dan otentik yang tak pernah terdistorsi oleh kepentingan apapun. Pemahaman demikian yang nantinya akan melahirkan adanya dikotomi epistemologis, antara aspek intuisi dan aspek materi. Aspek intuisi adalah nilai yang berkait dengan hubungan dengan Sang Khaliq yang pada proses selanjutnya menjadi teologi (kalam). Ini kemudian dimaknai sebagai aspek normatif. Domain inilah yang senyatanya tak boleh disentuh (unthouchable). Aspek material keberagamaan selanjutnya berujud hukum yang meregulasi setiap perilaku beragama umat Islam (Fiqh). Fiqh sebagai aspek material agama, lebih adaptif terhadap setiap perubahan. Kendati demikian, ia ternyata tak dapat melepaskan begitu saja pengaruh warisan lama. Sehingga yang terjadi adalah produk hukum yang sekedar menjadi catatan kaki dari ulama klasik skolastik. Sementara keyakinan (teologi) yang diyakini otentik tanpa cacat dan fiqh yang tak dapat keluar dari hegemoni lama, diwaktu yang sama hampir tidak dapat lepas dari perlombaan ideologis untuk mendominasi. Konsekwensinya, agama menjadi milik otoritatif pihak paling berkuasa. Belum tuntas persoalan diatas disikapi, disisi lain, bila melanjutkan pengembaraan sejarah, khususnya konteks sosio-historis masa khilafah pasca Rasul, niscaya akan ditemukan berbagai interpretasi nilai berbeda-beda yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kepentingan kekuasaan dan politik dengan berbagai rasionalisasi, provokasi dan agitasi. Interpretasi nilai keberagamaan masa klasik itulah yang saat ini mereka warisi, mereka kukuhkan dan mereka jadikan nilai absolut diatas segalanya.
Syari’at dan Ilmu kalam; Ortodoksi Nalar Islam Ketika Nabi wafat, para sahabatpun bertengkar tentang siapa yang berhak menggantikan kepemimpinannya terhadap tata sosial Islam dan atas dasar apa si pengganti berhak disebut ‘pemimpin Islam’. Terlihat episteme yang mulai berubah, era yang mulai bergeser. Terdapat suatu diskontinuitas, dari sebuah situasi yang penuh persatuan dibawah payung otoritas pengikat berupa single figure nabi, ke sebuah situasi penuh konflik politis untuk berebut klaim kebenaran sebagai ‘pengganti nabi. Sampai akhirnya terpilih Abu bakar sebagai Khalifatu Rasulillah melalui kesepakatan yang tidak begitu bulat. Inilah awal lahirnya ruang ‘epistemologis baru’ untuk benar-benar menghadirkan sosok pengganti nabi yang otoritatif memegang kebijakan politik sekaligus kebijakan agama. Banyaknya pihak yang pro-kontra, baik dalam mengukuhkan maupun melunturkan lembaga kekhalifahan, masing-masing saling berlomba menunjukkan bahwa klaimnya yang paling benar. Mulai saat itu apa yang disebut ortodoksi, klaim tentang ajaran yang benar dan murni mulai dikonstruksi dan dibangun. Sejak itu pula muncul aspirasi pembukuan Alqur’an dan penulisan sabda-sabda nabi yang nantinya akan dijadikan dasar pijakan berperilaku dan berkeyakinan kaum muslimin. Inilah yang pada dasarnya disebut Syari’ah. Ortodoksi pada akhirnya menemukan bentuknya yang sistematis terutama ketika pasca perang Shiffin dan peristiwa Tahkim di Daumatul jandal. Muawiyah yang pada waktu itu merupakan musuh politis Ali bin Abi Tholib, mencapai kemenangannya. Sehingga ia mendirikan kerajaan Islam dibawah panji bani Umayyah. Sejak kekhalifahan bani Umayyah inilah pengelompokan-pengelompokan politik tidak hanya menggunakan pedang untuk mengalahkan lawan, tetapi melalui serangan simbolik. Dengan rumusan-rumusan tertentu terhadap konsep iman (aqidah), masing-masing kelompok menyerang rival politiknya sebagai kafir. Lahirlah kemudian kelompok-kelompok keyakinan seperti Khawarij, Syi’ah, Mu’tazilah dan Sunni. Masing-masing sekte juga mempunyai kelompok-kelompok lebih kecil. Fenomena ini yang nantinya melahirkan disiplin ilmu kalam sebagai kerangka epistemology umat dalam mempersepsi Islam. Sehingga perlu ditegaskan bahwa keyakinan yang diklaim murni dari masing-masing golongan pada dasarnya berawal dari tarik ulur politis yang berkepanjangan ditubuh umat Islam untuk mencapai kekuasaan. Glorifikasi sejarah dalam Pendidikan Islam Stagnasi bangun epistemologis pemikiran Islam tidak lain disebabkan oleh kecelakaan sejarah (historical accident) masa klasik skolastik seperti yang ditipikal oleh Azumardi Azra. Sebab ketika otoritas kekhalifahan bani Umayyah mulai luntur dan bani Abbasiyah menjadi rezim, paradigma rasionalistik dari aqidah yang menggunakan penalaran burhani didekonstruksi oleh wacana baru berupa hukum-hukum fiqh yang menggunakan penalaran bayani. Disini akal yang awalnya dijadikan pencari kebenaran utama diposisikan menjadi instrumen kedua setelah teks-teks dogmatikal, baik rujukan secara langsung dari Alqur’an maupun hadist-hadist nabi yang dianggap shahih. Seiring dengan pecahnya bani Abbasiyah ke dalam bentuk kerajaan-kerajaan daerah (muluk Attawaif), disiplin fiqh yang formalistik pun mendapat tandingan dengan merebaknya sufisme yang berparadigma irfani. Pada saat itulah pergulatan ortodoksi-ortosoksi besar antara yang perparadigma burhani, bayani dan irfani saling mempengaruhi, mempersilangkan dan memperlawankan dan menjadi tumpang tindih. Dengan demikian, seperti ungkap Jadul Maula dalam salah satu makalahnya yang disampaikan dalam belajar bersama LkiS, bahwa historiografi pun mengalami kepenuhannya didalam persaingan untuk turut ‘menghadirkan’ masa kenabian. Dalam situasi persaingan yang keras dengan ‘masa nabi’ sebagai salah satu basis legitimasi yang dipertaruhkan, maka tak heran kalau historiografi yang lahir adalah sebuah praktek glorifikasi. Sementara itu, bila persaingan-persaingan penguasa untuk memperebutkan kekuasaan menggunakan legitimasi simbolik sebagai ideologi, maka wajar bila pada saat yang sama resistensi perlawanan rakyat melahirkan ideologi-ideologi lain, heterodoksi, dan bid’ah-bid’ah sebagai sumber kekuatan spiritual. Nah, ditengah-tengah kecamuk persaingan sengit menghadirkan masa kenabian itu, sebaliknya yang terjadi justeru pengaburan masa lalu. Pengaburan masa kenabian akibat tarik ulur kuasa ini bahkan sampai pada keadaan yang tidak mungkin dijernihkan lagi. Lalu dalam konteks sejarah yang sedemikian kompleks tersebut, posisi teologi yang saat ini dikukuhkan oleh lembaga pendidikan Islam sebagai manifestasi epistemologis dengan demikian tak lebih menjadi sisa-sisa tarik ulur kuasa masa lalu. Sebab ternyata paradigma yang dibangun oleh pendidikan Islam sendiri tak jauh dari penakaran dan pengusungan secara total pemikiran masa klasik tersebut.
Beban Epistemologis Pendidikan Islam Posisi sedemikian tinggi yang ditempati oleh corak pikir era klasik-skolastik seperti yang tergambar dalam uraian diatas lebih berefek pada pengukuhan tradisi tersebut menjadi semacam disiplin ilmu yang taken for granted. Disisi lain, kerangka pikir akademis, dengan masuknya disiplin ilmu modern seakan tak punya penetrasi untuk mengatakan ‘tidak’ terhadap cara analisis positivistik. Sehingga setiap pengetahuan keagamaan, kalau tidak mengadopsi cara lama, akan mengidap penyakit positivisme ini. Sebab disiplin ini lebih memposisikan Islam dan khazanah tradisinya sebagai the other. Karena menjadi ‘yang lain’, maka Islam hanya dijadikan obyek yang diposisikan stereo-tipikal. Pelebelan negatif selanjutnya tak dapat lepas dari kerangka keilmuan ini. Ternyata kedua disiplin ilmu ini, baik pendekatan tradisional maupun paradigma positivistik, sama-sama menjadi menara gading yang niscaya diruntuhkan. Nah, dalam posisi ini paradigma epistemologis dalam Islam menjadi sangat dilematis. Dan bila tidak beranjak dari kungkungan disipliner tersebut, akankah epistemologi pendidikan Islam dibiarkan absurd, baur dan stagnan? Zainal Lutfi |
Studi Agama Di Indonesia Dan Mimpi Akan Wilayah Normativitas |
Eh ada yang asyik nih surfing di internet malah dapat duit, kalo pingin, daftar disini
Eh ada yang asyik nih surfing di internet malah dapat duit, kalo pingin, daftar disini

